
Berita For4D – Menjadi politisi adalah menjadi ‘binatang politik’ (political animal/zoon politicon), demikian kata filosof fenomenal asal Yunani, Aristoteles. Mengapa? Karena, yang membedakan binatang dengan manusia, salah satu yang utama, adalah politik. Binatang tak berpolitik, sementara manusia justru sebaliknya. Karena itulah lahir istilah binatang politik tersebut. Memang bunyinya sangat tidak enak didengar, bahkan boleh jadi menjijikkan. Namun saya rasa, setelah kita memahami maksud atau raison de’tre-nya, cukup masuk akal terminologi tersebut disematkan kepada para politisi.
Setidaknya dari perspektif idealitas teoritik, melalui jalur politik, para politisi memperjuangkan hal-hal yang mereka anggap mulia sekaligus yang menjadi tujuan besar semua lapisan rakyat yang diwakilinya, seperti keadilan, kesejahteraan, keamanan ataupun kebahagiaan bersama. Dalam proses perjuangan tersebut, manusia bisa melakukan apa saja agar semakin dekat dengan tujuannya. Mulai dari menggandeng sesama manusia yang memiliki tujuannya yang sama, lalu meninggalkannya di jalan setelah tak dibutuhkan lagi. Atau menjatuhkan orang-orang yang kemungkinan akan mempersulit tercapainya tujuan tersebut, atau pula dengan mengubah aturan-aturan main yang dianggap kurang produktif atas tercapainya tujuan, dan lain sebagainya.
Semuanya biasanya dilakukan oleh manusia dalam rangka berpolitik. Dalam beberapa kajian, karena faktor perkembangan politik yang kian pragmatis, politik didefinisikan secara agak negatif pragmatis. Sebut saja pengertian politik dari pakar politik Harold Laswell, misalnya. Beliau memberi makna praktis pada politik hanya sebatas soal “siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana (who gets what, when, and how). Sebagian lagi, generasi awal penganut mazhab behavioralisme, seperti pakar politik dari University of Chicago , David Easton, memaknai politik dalam kerangka yang lebih fungsional.
Beliau menyebut politik sebagai segala upaya untuk mendistribusikan nilai-nilai (kesejahteraan, keadilan, kemaslahatan, dan lain-lain) secara otoritatif. Entah bagaimana cara kita memandangnya, jika kita bertanya kepada para politisi di partai politik atau parlemen, misalnya, politik bagi mereka adalah tentang bagaimana agar partainya menang pada pemilihan selanjutnya dan menempatkan sebanyak-banyaknya wakil di kursi-kursi yang ada di parlemen. Dan hasil termanis selanjutnya bagi mereka adalah bahwa mereka berhasil menjadikan politisi andalannya sebagai presiden atau menteri-menteri dalam kabinet.
Lantas, setelah itu, apakah mereka akan melakukan pendistribusian nilai-nilai tersebut? Saya kira, hal tersebut akan jadi topik lainnya, tentu dengan catatan, jika mereka masih ingat. Berbeda kasus, misalnya, saat kita bertanya pada para politisi di Palestina atau para politisi pejuang di era prakemerdekaan Indonesia. Bagi mereka, politik adalah jalan menuju pembebasan. Bebas dari penjajahan, bebas dari kolonialisme dan aneksasi negara lain atas negara mereka. Begitu pula jika kita tanya kepada politisi-politisi Papua pro Indonesia, misalnya. Bagi mereka, politik adalah membesarkan Indonesia di negeri Papua, agar kehadiran negara Republik Indonesia bisa dirasakan oleh segenap masyarakat ‘Bumi Cenderawasih’ Papua. Pada kedua contoh terakhir, sangat jelas terlihat siapa dan apa yang sedang mereka perjuangkan.
Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan politisi-politisi Indonesia saat ini? Lebih spesifik lagi, bagaimana dengan capres-cawapres kita yang akan berlaga pada Pemilu 2024 nanti? Bagaimana dengan “constitutional dan political engineering” yang dilakukan oleh salah satu kubu pasangan capres-cawapres baru-baru ini? Cukup disayangkan memang, dunia perpolitikan kita agak kurang ideal penampakannya. Saat ini, kontestasi untuk posisi presiden, misalnya, sudah dimulai dengan intrik politik ‘kacangan’, yang kental dengan pertimbangan pragmatis di satu sisi dan minus spirit kenegarawanan di sisi lain. Bahkan, semangat penguasa dan salah satu pasangan capres-cawapres yang didukung penguasa sudah masuk kategori terlalu ambisius, yakni ingin memastikan diri menjadi pemenang, jika perlu sekali putaran, jauh hari sebelum kontestasi dimulai. Ambisi yang berlebihan tersebut mulai terlihat dari obrolan dan temuan banyak kalangan di ruang publik.
BACA JUGA : Sebelum Bayi di Cianjur Hilang, Ada Mobil Avanza Berhenti dan Anjing Mengonggong
Demikian pula dengan obrolan di media sosial terkait penggunaan beberapa institusi negara dalam mengekang gerakan politik lawan, seperti penggunaan institusi pemerintahan untuk membersihkan alat peraga lawan. Bahkan untuk beberapa kasus, sudah hampir mirip intimidasi politik, seperti yang dialami DPC PDIP Solo belum lama ini. Namun hal tersebut nampaknya hanyalah kelanjutan dari rekayasa politik di level atas, dengan menggunakan beberapa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan pasal yang menguntungkan kepentingan politik salah satu kandidat. Faktanya sudah tak bisa dibantah lagi, karena Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadikan tameng politik hukum penguasa nyatanya pada akhirnya diputus telah melakukan kesalahan etis fatal oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), tapi tidak membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh MK sebelumnya. Dan jika dilihat lebih jauh ke belakang, putusan MK yang menguntungkan anak presiden dan bakal capres Prabowo Subianto adalah buah minimalis dari berbagai upaya ‘pembusukan’ institusi demokrasi yang sudah dilakukan penguasa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode
Beruntungnya, publik Indonesia masih memiliki kesadaran demokratis yang cukup tinggi untuk menolaknya. Berlatar upaya-upaya politik naif di atas, nampaknya proyeksi demokrasi kita ke depan akan semakin suram. Karena itu publik dan masyarakat sipil harus mulai banyak melibatkan diri di dalam mengawasi praktik-praktik politik yang sedang berlangsung, agar tidak terlalu jauh melenceng dari idealitas demokrasi yang kita harapkan. Sebagai ilustrasi sederhana, mari kita asumsikan jika Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menang, misalnya. Lalu Prabowo akan berkuasa selama lima tahun ke depan. Karena faktor umur, misalnya, Gibran kemudian maju sebagai calon presiden 2029, dengan dukungan penuh dari kekuasaan presiden yang sedang berkuasa, yakni Prabowo Subianto. Dengan kata lain, diperkirakan nanti Prabowo juga akan memainkan kartu yang persis sama dengan Presiden Jokowi hari ini, untuk memenangkan Gibran. Lalu jika Gibran menang, maka diasumsikan 10 tahun lagi setelah 2029 nanti dinasti Jokowi akan tetap berkuasa, setelah lima tahun sebelumnya juga berkuasa dalam kapasitas sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto. Pun selanjutnya diasumsikan bahwa di tengah jalan saat Gibran berkuasa, ada putra Presiden lainnya Kaesang Pangarep dan sang menantu Bobby Nasution yang sudah antre di barisan penerus Gibran.
Lagi-lagi diasumsikan bahwa keduanya bisa membuat komitmen untuk berbagi waktu berkuasa, misalnya Bobby untuk 5 tahun, lalu setelah itu Kaesang 10 tahun selanjutnya. Maka lengkap sudah, keluarga Jokowi akan bisa berkuasa lebih lama dibanding dinasti Presiden Soeharto di Indonesia. Inilah ilustrasi proyeksinya ke depan jika pemilihan presiden kali ini semata-mata dihitung secara elektoral dan melupakan moralitas kenegarawanan seorang pemimpin. Spirit bagi-bagi kuasa akan menjadi motivasi utama dalam merebut dan mempertahankan singgasana di Istana. Silahkan dibayangkan sendiri. Padahal, selain urusan elektoral, kita berharap bahwa seorang presiden yang sedang menjabat, lalu seorang bakal calon presiden dan seorang bakal wakil presiden yang akan berlaga, bukan hanya seorang politisi handal dan licin, tapi juga seorang negarawan yang menempatkan konstitusi di dalam hatinya dan memperjuangkan kepentingan publik di dalam tindakan dan kebijakannya.
Oleh karena itu, tugas kita saat ini adalah bagaimana caranya agar harapan itu bisa tetap dijaga dengan baik alias tidak pelan-pelan berubah menjadi mimpi, mimpi yang hanya bisa diraih jika kita semua tertidur lelap. Sebagaimana pernah saya ingatkan di artikel terdahulu, kekuasaan memang berpeluang menjadi sangat berbahaya jika dipegang oleh anak muda yang kurang bijak, kurang pengalaman, dan kurang memahami nilai-nilai kenegarawanan. Banyak yang berargumen untuk menanggapi pernyataan saya tersebut dengan mengatakan bahwa anak Presiden Rodrigo Duterte di Filipina adalah preseden dan referensi yang bisa dijadikan pembenaran atas apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto dalam mendorong Gibran secara cepat ke panggung politik nasional. Namun perbandingan tersebut perlu dilihat secara mendalam dan detail, agar tidak terjebak ke dalam perbandingan yang sifatnya “pukul rata” tanpa tedeng aling-aling. Salah satu contohnya adalah bahwa Duterte tidak memulainya dengan grasah-grusuh wacana tiga periode. Lalu, di sana tidak ada rekayasa konstitusional yang dilakukan secara cepat dan sistematis, yang menjadi prasyarat agar putri Duterte bisa maju sebagai bakal calon wakil presiden.
Yang lebih penting, tidak ada anak Duterte lainnya yang melalui karier politik secepat kilat untuk menjadi ketua umum parpol, yang akhirnya juga digunakan untuk mendukung pencalonan kakaknya. Pun yang tidak kalah krusial adalah bahwa demokrasi di Filipina tidak lebih baik dari Indonesia. Politik keluarga sudah sedari dulu eksis di sana, berbarengan dengan relasi patron-klien antara penguasa di Istana Malacañang di Manila; istana kepresidenan yang bergaya bahay na bato dan neoklasik yang merupakan kediaman resmi Presiden, dengan jejaring penguasa lokal di seluruh Filipina, yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa sistem politik demokratis semakin sulit untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di Filipina. Jadi dalam hemat saya, agak kurang tepat menjadikan Rodrigo Duterte dan anaknya Sara Duterte-Carpio, misalnya, sebagai pembenaran. Karena dengan kualitas demokrasi yang sejatinya berada di bawah Indonesia, Duterta tidak melakukan rekayasa atas institusi demokrasi yang ada dan utak-atik konstitusi dalam waktu cepat untuk kepentingan politik dirinya dan keluarganya. Apalagi, dari sisi track record pribadi, anak Duterte nampaknya cukup layak untuk dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden kala itu mendampingi calon presiden yang adalah putra mantan Presiden Ferdinand Marcos, yaitu Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Jr. Seperti ayahnya, Sara Duterte-Caprio sempat menjadi pengacara sebelum terjun ke dunia politik pada 2007. Sara yang digembleng ayahnya sebagai pengacara, pertama kali tancap gas di jalur politik ketika terpilih menjadi wakil wali kota Davao, mendampingi ayahnya yang kala itu menjabat sebagai wali kota Davao.
Namun kemudian, Sara Duterte-Caprio melanjutkan kariernya di kancah politik pada 2010, saat ia menggantikan ayahnya menjadi wali kota perempuan pertama di Davao. Pendek kata, kembali ke masalah diktum kekuasaan di atas sebenarnya berlaku untuk semua umur. Tidak hanya untuk anak muda, tapi juga untuk semuanya. Karena pada dasarnya, sebagaimana diingatkan oleh Sejarawan Inggris Lord Action, bahwa “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Dengan kata lain, jika sebelum berkuasa saja rekayasa-rekayasa dan intrik-intrik politiknya sudah seperti itu, apalagi jika sudah berkuasa alias sudah menjadi dwi tunggal penguasa. Sinyal-sinyal politik yang mengindikasikan prospek kurang baik pada masa depan demokrasi kita tentu perlu sama-sama dicegah keberlanjutannya secara bersama-sama dengan niat demi kepentingan masa depan bangsa. Para elite dan berbagai elemen masyarakat tentunya perlu melakukan komunikasi secara baik dengan pemerintah dalam rangka menyampaikan pesan agar tidak terjadi “misuses of power”, agar tidak terjadi keberpihakan secara terangan-terangan dari kekuasaan yang sedang berkuasa kepada salah satu kandidat, dan agar netralitas aparat pemerintahan juga bisa tetap terjaga. Semoga!





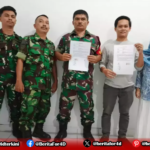

















+ There are no comments
Add yours